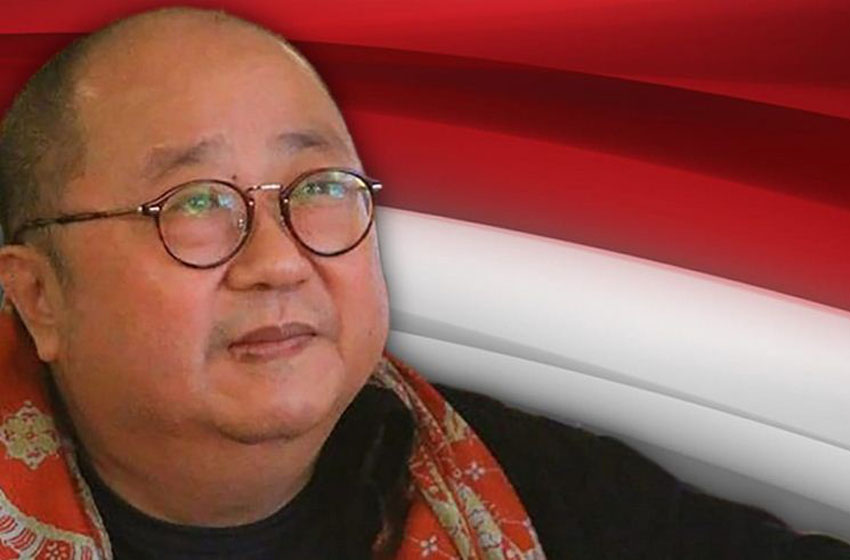Kolom
Kuantar Sampai Liang Lahat

Kematian adalah peristiwa biasa di muka bumi. Namun bagi keluarga terdekat seperti tragedi besar. Tentu hal ini dialami banyak orang yang apabila salah satu anggota keluarganya wafat, pasti berduka. Meski kematiannya wajar karena sakit. Bukan akibat bencana, kecelakaan, ataupun tindak kejahatan.
Lewat apa pun kepergian insan ke alam malakut, tampaknya selalu ada rentetan kejadian yang mengiringinya. Dan seringkali tak disadari tanda-tandanya, kendati bersitan di hati kadang nyata. Sehingga meninggalkan pilu, sesal, dan tentu deraian air mata. Begitupun yang saya alami hampir setahun silam.
Saya ingin menuangkan pengalaman di hari-hari yang terasa panjang setelah kematian suami. Dan tentu berharap ada hikmah di kemudian hari. Saya seperti terpenjara oleh perasaan diri sendiri. Penjara duka yang sempat membelenggu keseharianku. Saat itu pula terdorong keinginan menulis, untuk menghibur diri, tapi tak mampu. Dan hari ini baru bisa menuangkannya.
Ketika sedang mengalaminya, serasa mimpi, padahal nyata. Yang hidup akhirnya fana, dan fana itu nyata. Jasad itu diam, tak bergerak. Dan abadi. Padahal empat hari sebelumnya masih bercanda-ria dan membuatku terpingkal-pingkal. Beberapa jam lalu juga masih minta minum dan mengunyah buah segar.
Mengingat semua itu semakin menikamkan luka. Dan anehnya di saat demikian, segala yang jauh berlalu datang membayang. Kembara pikiran jadi liar, dan segala rasa teraduk-aduk dalam emosi yang seakan menggali duka kian dalam.
Ketika menuju rumah sakit, kakinya di pangkuanku. Dia duduk selonjor menyita jok tengah dengan punggung bersandar di dinding mobil. Dan ketika kembali ke rumah, aku harus membiarkan dia di belakangku. Terbujur kaku di dalam keranda. Sementara aku duduk di samping sopir. Tak ada yang lain lagi di ambulan itu.
Sesekali aku menoleh ke belakang. Ke keranda bertudungkan kain warna hijau itu. Tanpa tetesan air mata. Apalagi sesenggukan. Aku seperti perempuan yang tegar, kendati bayangan saat berangkat ke rumah sakit silih berganti dengan kondisi saat itu, dengan jasad di belakangku.
Tiba di rumah, para tetangga sudah menyiapkan semuanya. Jenazah segera dimandikan. Keluarga dekat diminta pak ustadz untuk menyiramkan air bunga. Itulah terakhir kali aku melihat wajah dan badan wadag suamiku. Ruhnya entah dimana. Terasa masih dekat denganku. Masih di rumah.
Beberapa hari aku merasakan ia tak kemana-mana. Kendati kusaksikan dengan mata kepala bahwa badan wadag yang terbungkus kafan itu dimasukkan ke liang lahat lalu diurug tanah pekuburan, ditaburi aneka bunga. Batu nisan bertuliskan hari kelahiran dan kematiannya terpasang pula.
Membaca nisan itu, lagi-lagi perasaanku seperti mimpi. Manusia, kalau sudah sampai azalnya, kemana pula harus pergi, kalau bukan kembali ke asal. Jasad masuk tanah, dan ruh sesuai keyakinan dan pengetahuan kita yang sedikit ini kembali ke alam kelanggengan. Ke jagat nan abadi.
“Sabar ya. Tabah! Semua akan mengalami,“ Ini kata-kata yang berseliweran, diucapkan keluarga yang datang, juga para tetangga dan handai tolan.
Ya, itu ucapan klise dan menjadi semacam ritual rutin bagi orang-orang yang takziah. Namun bagi keluarga yang ditinggalkan, kata-kata penghiburan itu menjadi sangat bertuah, serupa doa yang membesarkan jiwa.
Aku baru bisa menangis saat pembacaan doa dalam tahlilan selepas maghrib. Seperti disadarkan kembali bahwa dia sudah tiada. Dalam doa bersama itu, dia sudah disebut/dipanggil arwahnya saja, ruhil ahlil kubur.
Keesokan hari, hingga beberapa hari ke depan, kondisiku seperti rapuh. Tak ada selera makan, pun tak ada rasa lapar. Anak-anak dan keluargalah yang selalu mengingatkan. Juga teman-teman kendati lewat pesan singkat.
Berdialog dengan “kata kematian” merupakan keasyikan tersendiri saat itu, meskipun dalam rasa duka yang dalam. Ikhlas dan sabar, adalah bahasa doa yang selalu kupanjatkan. Dan tentu istigfar, mohon ampun pada Illahi atas kesalahan almarhum dan juga keluarga yang ditinggalkan.
Aku menjadi ingin tahu perasaan ibu-ibu dan saudara dan siapapun yang telah ditinggalkan oleh pasangannya. “Memang begitu, tak mudah melupakan. Hanya waktu yang akan mengobati.” Itulah jawaban yang sering terlontar.
Dalam istilah Jawa, istri/suami disebut garwa. Akronem dari sigarane nyawa. Belahan jiwa. Seperti dalam lagu, separuh jiwaku pergi menghadapi kematian itu. Ya, terasa ikut melayang. Tak kubayangkan aku akan jatuh dalam kepedihan yang dalam.
Selama ini aku menganggap kematian itu keniscayaan. Kepastian. Siapa pun akan mengalami. Jika tak mau ditinggalkan, tentunya meninggal terlebih dulu. Namun tak kusangka, bahwa kepedihan itu langsung bersarang dan menghujam di kalbu. Ibarat elang, sayap-sayapku patah. Terasa rapuh benar ketika itu. Hanya harapan yang terus kupupuk, kugantang dan kupatri dalam pikiranku bahwa aku akan baik-baik saja. Tuhan akan mencabut dukacita ini.
Benar. Seiring pergantian siang dan malam, pekan demi pekan berulang dan bulan pun berubah, kesedihan itu menghilang. Sabar dan ikhlas bak khasanah kata yang serasa bisa ter-update setelah berhari-hari dalam pagutan duka. Bahkan terbitnya fajar dan corat-coret arunika di langit Timur seperti membawa harapan baru dan semangat baru. (iswati)