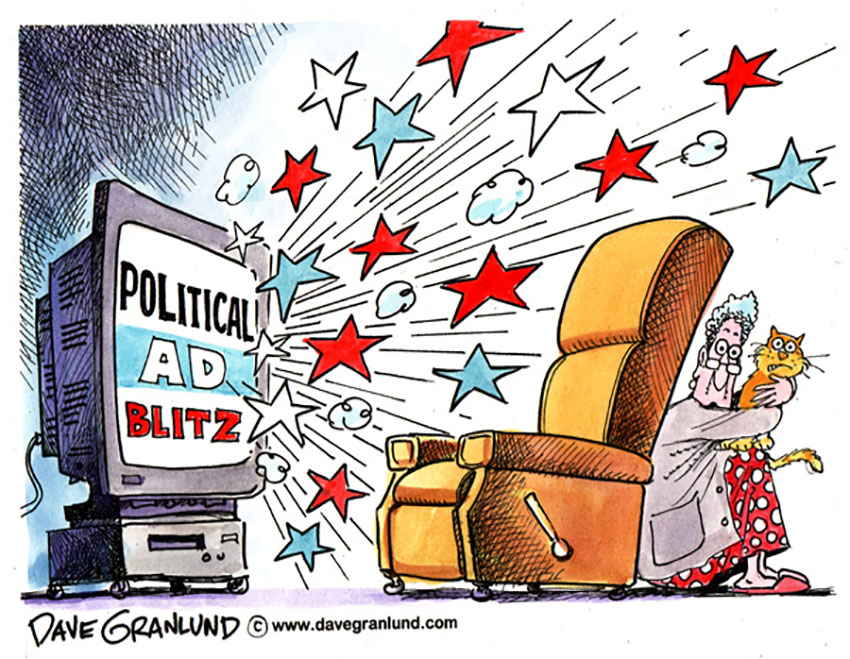Kabar
“Tilik” Generasi Baru Film Pendek Indonesia

Catatan: Bambang J. Prasetya
“How Millennials Kill Everything” ini judul tulisan yang kerap berseliweran grup WA. Isinya tak lain menyorot betapa milenial adalah ‘pembunuh berdarah dingin’, yang membunuh apa pun. Pelan tapi pasti kenyataannya pun menguatkan kebenarannya semakin menjadi.

Era distruption (distruptif) yang nggegirisi, jika lengah menyikapinya. Tapi tak perlu risau resah gelisah, setiap generasi pasti punya caranya sendiri dalam merespon jamannya. Demikian pula setiap generasi baru akan hadir bersamaan kemajuan jamannya, termasuk generasi melinial. Setiap tesis akan melahirkan anti tesa, tesa, sintesa, yang akan saling berkaitan terus berlanjut berputar kemana arah peradaban berlangsung. Sejarah telah begitu banyak menuliskan peristiwa-peristiwa transformatif perubahan semacam, dari revolusi sosial sampai teknologi.
Millenial memang progresif, begitu kesan subyektif, ketika sebuah komunitas film independen Jogja yang rata-rata beranggotakan millenial militan, film maker ideologis, mengajak untuk nonton dan ngobrolin film “Tilik”. Kesan terkuatnya hanya pada pilihan penciptaan pengadegan di dalam truk yang melaju melewati beberapa hambatan, sesederhana itu responnya. Meski adegan semacam pernah pula dikerjakan banyak kelompok lain, almarhum Hendro Suseno dan pantomimer kondang Jemek Supardi, pernah bikin performance visual didalam gerbong kereta yang melaju menuju Jakarta misalnya, atau kelompok teater yang bikin pertunjukan didalam bus kota keliling Jogja, juga video performnace art ‘Lesung Dance On The Truk”. Lha mengapa “Tilik” mengesankan? Karena mampu memproyeksikan secara baik lokalitas Jogja kedalam potret negeri +62 termutakhir. Bahwa filmnya kemudian ternyata booming, trending, viral dan out of the box, adalah bagian lain diluar ranah struktur film yang malam itu dibincangkan.
Menyaksikan ‘mise en scene’ truk sepanjang lebih separo dari durasi film. Mengajak untuk membayangkan secara imajinatif bagaimana potret negeri +62, semirip seperti peristiwa yang terjadi dalam truk film tersebut. Penuh mayoritas atribut agamis, tapi nyinyir membincangkan soal yang sebaliknya, profanik. Potret realitas (kita) di ruang sosial yang nyinyir, bawel, ghibah, julid, narsis, dan riya. Sedangkan yang di luar mainstream, minoritas, harus bersabar ditengah hiruk-pikuknya dominasi relasi komunikasi. Sebutlah sebuah metafora yang gaduh. Menjauhi pendekatan isu perempuan yang termafum di Tagline judul filmnya. Selain secara keseluruhan tidak menunjukkan “ide” perempuan yang ingin disampaikan, kecuali penggambaran stereotipe.
Tentu, sekali lagi ini persepsi tafsir personal. Sebab apapun karya cipta seni tidak berdiri sendiri diruang kosong, lepas dari habitat sosialnya. Ditengah hangatnya situasi sosial politik polarisasi yang melahirkan dikotomi diametral sejak lima tahun terakhir ini. ‘Tilik’ menjadi semacam ‘alat’ representasi hasrat saling menohok kedua belah pihak: Togog-Kadrun, Cebong-Kampret. Namun diakui atau tidak, itulah fenomena generasi baru film pendek yang hidup bukan lagi dari pemutaran screening diskusi. Medsos lebih dari pada cukup memberikan mediasi aktualisasi sosialisasi ekspresi. Semuanya sangat tergantung kecakapan mengelola dan memanfaatkannya sebagai “sarana” ataupun “tujuan”, dengan indikator yang semakin jelas: subscribers, viewer, followers.
Jika mau ditarik diarena yang lebih lebar lagi, maka Pandemi Covid-19 memiliki kontribusi besar pula, mengapa kemudian publik lebih suka mencari hiburan film di media digital online semacam. Pada perspektif inipun tak terabaikan bagaimana nasib film sebagai produk industri hiburan yang sangat tergantung pada profil benefit-nya dari ticketing. Ketika jaga jarak social distancing, mengurangi mobilitas sosial di rumah saja, menghindari kerumunan dan tempat-tempat tertutup. Maka film bioskop bisa menjadi bernasib ‘riwayatmu dahulu’. Dan hal serupa pernah terjadi menerpa industri film tahun 50-60 an ketika industri teknologi televisi sedang naik daun.
Benar, dunia film pernah mengalami masa paceklik, karena munculnya teknologi tabung gelas televisi. Sampai industri film Hollywood kolaps ditinggalkan penontonnya ketika teknologi televisi berkembang pesat. Film mereka tidak lagi diincar oleh stasiun-stasiun televisi, yang dulunya berani membayar tinggi, untuk memutarnya pasca pemutaran bioskop. Jumlah penonton bioskop menurun hingga hanya satu milyar orang per tahun (jumlah yang kurang lebih konstan hingga awal 90-an). Mulai tahun 1969, perusahaan-perusahaan film Hollywood menderita kerugian $200 juta tiap tahunnya.
Generasi Movie Brats
Para produser Hollywood pun berpikir keras putar otak, tidak mau menyerah begitu saja. Salah satu strategi mereka adalah dengan memproduksi film-film yang bertemakan budaya tandingan (counter culture), yang ditujukan bagi generasi muda saat itu. Film sebagai film. Mereka adalah generasi pertama pembuat film Hollywood yang tidak datang melalui sistem atau melalui teater, novel atau televisi. Oleh berbagai kalangan generasi ini kemudian disebut sebagai Generasi Movie Brats Hitchcock (De Palma), Kurosawa (Milius) dan Walt Disney (Spielberg). Para sutradara-sutradara muda yang dijuluki movie brats ini, adalah mereka yang tidak lahir dari dalam sistem industri Hollywood, namun dari sekolah-sekolah film: NYU (New York University), USC (University of Southern California), dan UCLA (University of California: Los Angeles). Mereka tidak hanya menguasai mekanisme produksi sebuah film, tapi juga paham mengenai estetika dan sejarah film. Dan tidak seperti para sutradara generasi sebelumnya, para movie brats memiliki pengetahuan yang luas mengenai film dan sutradara-sutradara terkenal, termasuk mereka yang belajar di luar sekolah (otodidak).
Hal yang sama juga sempat terjadi di Indonesia, ketika film Indonesia benar-benar mati suri. Lalu sindikasi sineas muda yang kemudian melahirkan film Kuldesak (1998). Kerja keroyokan beberapa film maker muda itu cukup inspiratif menggugah semangat memproduksi film dalam negeri sampai hari ini. Gantian kemudian Pandemi Covid-19 menghentikan gairah bisnis gambar bergerak itu. Bagaimana tidak jika untuk mencapai BEP cost produksi tidak lagi mudah. Tentu ini soal yang harus dijawab kemudian secara serius. Meyakinkan penonton agar mau datang ke bioskop, belum lagi protokol kesehatan yang harus meminalisir kapasitas kursi gedung. Rasa-rasanya untuk menghabiskan sebuah film menjadi box-office pun butuh prasyarat perhitungan baru. Begitulah New Normal menuntut penyikapan untuk melakukan reformating seluruh aspek yang terkait.
Literasi pastilah. Betapapun tidaklah mudah dilakukan diera ‘dunia yang terbuka’ hari ini, namun kehadiran dan keperpihakan negara tetap diperlukan. Instrumen untuk menjaga, melindungi serta mensetarakan masyarakat warga negaranya lewat berbagai kebijakan yang ada. Walaupun tidak semua kebijakan bisa mengikuti kecendrungan pasar atau bersifat liberal. Ditengah tuntutan, tepatnya desakan kapitalisasi yang terbuka, negara diharapkan pula tetap kukuh dalam mendahulukan kebijakan deliberatif. Selayaknya Fasilitator-Katalisator yang mampu menjembatani problem masyarakat, menyoal distribusi akses dan aset. Sebagaimana esensi reformasi menjaga demokrasi yang tetap tegak lurus. Menandaskan tiga azas demokratisasi: Sharing Kekuasaan, Distribusi Ekonomi dan Memberdayakan Masyarakat, yang kesemuanya bermutasi pada peran masyarakat, termasuk ruang publik.
Negara bukan katalis snobisme atau sekedar menjadi followers mengikuti trend zaman. Apalagi lemah dihadapan Heater, Headspeet, Busser, Nitizen, Facebooker, YouTuber, Selebgram, influencer yang menyelundupkan berbagai ide gagasan kepentingan ideologis, ekonomi bahkan Lifestyle lewat semburan Hoax atau Firehouse. Jika dianalogikan dengan diksi ‘perang’, inilah sesungguhnya ‘proxy war’ itu. Terhadap akselerasi transformasi yang tak terelakkan dan memunculkan distingsi yang memerlukan keselarasan yang berkeadilan, dari situlah pentingnya negara diperlukan hadir mengayomi masyarakat warga negara. Betapapun perubahan dan akselerasi IPTEK sebuah keniscayaan.
Media Baru Film
“Evolusi Ekologi” media yang ditandai dengan transisi masyarakat dari pengguna media lama (old media) menjadi pengakses media baru (new media) menuntut adaptasi dan intervensi. Karena dunia media secara keseluruhan adalah sebuah struktur yang berlapis (multilayer structures), adaptasi dan intervensi mesti dilakukan pada level yang berbeda pula. tulis Dr. Agus Sudibyo, mengantar bagaimana membangun struktur ideal integrasi media. Dari sana pula muncul kesadaran bahwasanya tanpa ingatan sejarah yang baik, kita akan gagal membayangkan masa depan secara jernih. Jika tidak ingin hanya menjadi buih yang melompat dari arus ke arus berikutnya, “viral” ke ‘viral’, dari trending ke trending, dari “isu” ke ‘isu’, dari “aktual” ke ‘aktual’, dari “update” ke ‘update’, dari “up-to-date” ke ‘up-to-date’, dan lupa mengingat ada berapa sudah patahan riak gelombang dilewati, kecuali nanti mengharamkan jejak digital.
Sebelum Covid-19 saja, banyak yang masih menyandang kesulitan, untuk survive tiap hari aja harus mau jungkir balik, termasuk membalikkan kenyataan biar tetap tampak gagah dan mempesona. Antara yang berhutang dan dihutangi, bisa saling toleransi. Ada speleng margin untuk memberi kelonggaran pada yang berhutang. Tapi kini, semua membutuhkan, karena situasi yang sulit, stack berhenti. Gulung lipat nir pendapatan. Wajarlah klo harus menagih. Mungkin itu pulalah yang menjadi alasan mengapa salah satu kreteria bisnis tontonan harus kontenable. Meskipun ekspresinya bisa macam-macam, sesuai dengann perspektifnya sendiri-sendiri.
Popularitas memang sedang menjadi arus keutamaan. Kualitas kadang seolah mustahil diperdebatkan ulang, tak usahlah gegabah menyebutnya sebagai degradasi atau reduksi. Masih ingatkan, ini mazabnya kebenaran paska kebenaran, post truth, pemegang otoritas dialah penentuannya. Kuasa dominan itu. Faktanya kembali pada soal di atas, pegiat medsos sekali lagi tengah menjadi orientasi tujuan sasaran sekaligus goalnya. Toh mereka juga representasi penerima manfaat atas nama publik. Karenanya bukanlah tabu jika untuk mengupgrade sebuah karya film penting disiapkan pula alokasi plafon beaya publikasi, jikalau dipandang perlu marketing buzz-nya. Namanya juga buzz promotions sekalian Stealth Marketing. Menjajagi interaksi persuasi, kemungkinan dialektika, bukan sekedar pencitraan, menginformasikan, mensosialisasikan, memahamkan, sebagai sebuah proses internalisasi. Diranah pasar, publik hanyalah riak buih yang digerus arus komersialisasi, konsumerisme, bagaimana pun melawan tetap harus mau hanyut tenggelam atau minggir tersisih. Industrialisasi materialisme kapitalisme itu esensi sesungguhnya, bukan kesepakatan terminologis, tetapi memang ‘basic want’ hampir kebanyakan insan yang jika dijamakan ‘public need’, lalu diargumentasikan secara persuasi di ruang interval dialektika.
Benar yang dimaui para nitezen. Konten digital itu kaidahnya gak rumit-rumit amat. Sederhana, ringkas, padat, mudah dipahami, unik, aneh, lucu, segar lucu-lucuan, mengena, menampilkan kebaruan, inovatif, alternatif baru, dan mengandung ikatan-ikatan sosial yang kuat, populer. Lalu apakah kemudian citra film pendek dikemudian hari hanya akan seperti itu? Tentu sangat tergantung para pelaku, film maker independen itu sendiri. Merekalah pemilik sah sejarah dan masa depan film selanjutnya, ditengah gempuran berbagai persoalan yang tidak sederhana lagi. Hanya saja bagi mereka yang mengenal kajian media dan budaya, maka tayangan apapun menjadi semacam ‘haram’ jika hanya dipahami sebagai hiburan semata. (*)
Bambang JP, Pemerhati dan Praktisi Media Seni Publik.