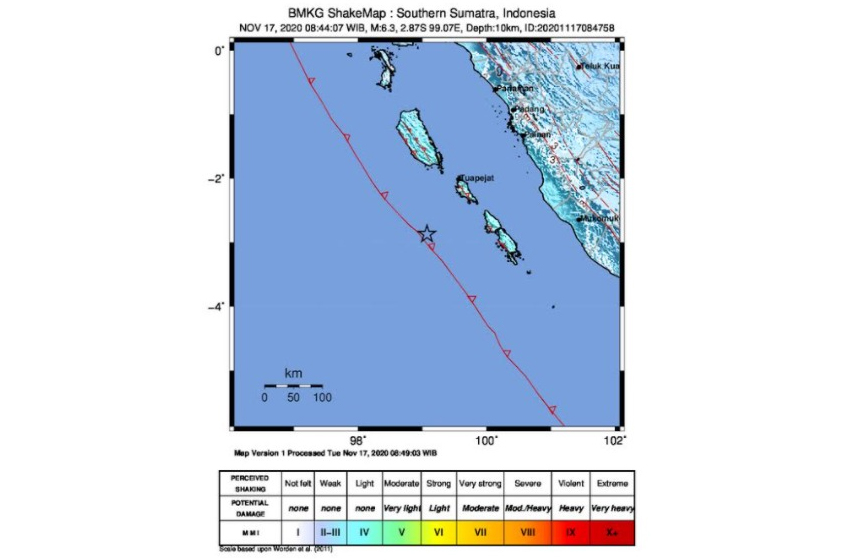Feature
Empat Sandal Jepit di Pedalaman Siberut


Kiri: Jalan di pedalaman Kepulauan Mentawai. Kanan: Penulis bersama anak-anak Sikerei Desa Rogdog, wilayah Madobag, Siberut Selatan. Foto: Istimewa
 PEMBANGUNAN infrastruktur yang digenjot pemerintahan Jokowi-JK, telah mencatatkan cerita manis nan fantastis. Dari sisi alokasi anggaran, jika tahun 2014 anggaran infrastruktur Rp 177 triliun, maka di tahun 2017 melambung menjadi Rp 401 triliun.
PEMBANGUNAN infrastruktur yang digenjot pemerintahan Jokowi-JK, telah mencatatkan cerita manis nan fantastis. Dari sisi alokasi anggaran, jika tahun 2014 anggaran infrastruktur Rp 177 triliun, maka di tahun 2017 melambung menjadi Rp 401 triliun.
Dalam tiga tahun terakhir, pemerintahan Jokowi-JK sudah membangun jalan baru sepanjang 2.612 kilometer, dengan rincian, tahun 2015 terbangun 1.286 km, tahun 2016 sepanjang 559 km, dan pertengahan 2017 sudah terbukukan panjang jalan baru 778 km.
Dari 2.612 km jalan baru tersebut, sekitar 2.000 km di antaranya merupakan jalan perbatasan yang dibangun di titik-titik terluar dan di pelosok Kalimantan, Papua, hingga perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) di Pulau Timor. Selain itu, pemerintah Jokowi-JK juga telah membangun jalan tol sepanjang 568 km, terbagi atas 132 km pada 2015, 44 km pada 2016, dan sisanya 392 km pada tahun ini. Pemerintah bahkan menargetkan pembangunan jalan tol hingga 2019 mendatang akan mencapai 1.851 km.
Menjadi ironis, jika menilik pembangunan infrastuktur jalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Ini adalah penggalan kisah perjalanan ke Mentawai, menjelajah Pulau Sipora, Pagai, Pagai Selatan, dan Siberut. Panjang jalan utama (beraspal) di masing-masing pulau, beberapa waktu lalu, tidak lebih dari 10 kilometer. Selebihnya? Jalan tanah berlumpur.
Kabupaten berbentuk gugusan kepulauan itu, sejatinya adalah “surga tertutup kabut”. Betapa tidak. Mentawai menawarkan semua jenis keindahan alam. Kekayaan ombak besar yang bergulung-gulung bisa dipastikan menjadi lokasi surfing terbaik di negeri ini. Almarhum aktor Paul Walker (Fast and Furious) termasuk salah seorang asing yang “memiliki” private resort di sana.
Bagaimana kita bisa menjangkau Kepulauan Mentawai? Jika kebanyakan lokasi wisata menawarkan “cara mudah” dan “cara susah”, sejatinya menuju Mentawai hanya ada satu cara: cara mudah. Dari Pelabuhan Bungus, Padang, kapal-kapal ro-ro siap mengantar ke Mentawai dengan waktu tempuh delapan jam.
Saat ini, bahkan sudah tersedia speed boat yang bisa memangkas waktu tempuh menjadi empat jam saja. Jika ingin lebih cepat, tersedia pula penerbangan perintis dari Bandara Internasional Minangkabau di Padang, langsung ke Bandara Rokot, Sipora. Hanya saja, jalur penerbangan perintis yang dilayani Susi Air itu, baru tersedia satu penerbangan dalam seminggu.
Cara “susah” baru didapat, manakala kita hendak mengunjungi suku pedalaman, di Siberut, misalnya. Alhasil, infrastruktur jalanan bisa saya setarakan dengan cucuran-peluh dan pengorbanan empat sandal jepit. Ini terjadi ketika Dinas Pariwisata Kabupaten Mentawai meminta saya menuliskan objek wisata daerah itu.
Seminggu di Mentawai, nyaris tak terasa. Kenangan pun terlontar pada agenda mengunjungi masyarakat adat di pedalaman Pulau Siberut. Dengan boat carteran, kami melompat dari Pulau Sipora ke Pulau Siberut. Yang kami tuju adalah Dewa Rogdog.
Ada dua pilihan mencapai Desa Rogdog, wilayah Madobag, Siberut Selatan. Yang pertama naik pompom, sebutan untuk perahu motor tempel. Yang kedua, naik ojek. Dengan pompom, perjalanan ke pedalaman Siberut bisa memakan waktu enam jam. Sedangkan dengan ojek, cukup tiga jam. Itu teorinya. Dengan jumlah peserta lima orang, dua di antaranya pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Mentawai, kami pun memutuskan mencarter ojek. “Lepas sepatu, beli sendal jepit minimal tiga pasang,” ujar tukang ojek.
Sampai di titik itu, saya benar-benar tidak paham, mengapa bekal menuju Desa Rogdog adalah tiga pasang sandal jepit. Niat mencari tahu, saya urungkan, karena khawatir kehilangan momentum yang mengejutkan di perjalanan nanti. Maka, saya pun membeli empat pasang sandal jepit. Tiga pasang memenuhi saran tukang ojek, satu pasang sebagai serep.
Deru knalpot yang dibobol, sungguh memekakkan kuping sepanjang perjalanan menuju pedalaman Siberut. Awal perjalanan cukup lancar. Jalanan masih beraspal. Rupanya, kenyamanan itu hanya berumur lima kilometer saja. Setelah itu, kami harus menyeberangi sungai.
Dari titik penyeberangan, hingga tiba di lokasi… adalah “perjuangan dan doa”. Dari total perjalanan tiga jam lebih, dua jam di antaranya harus kami lalui dengan berjalan kaki. Jalanan setapak, melewati hutan, ladang, yang di sana-sini dijegal jalan berlumpur. Belum sampai jarak satu kilometer dari bibir sungai tempat penyeberangan pertama, satu sendal “tenggelam” tenggelam di dasar lumpur. Oh… ini kiranya maksud si tukang ojek tadi.
Ada kalanya, jegalan lumpur di sepanjang perjalanan benar-benar tidak memberi pilihan. Hanya keberuntungan saja jika yang kita injak adalah lumpur berdasar batu atau potongan kayu. Sebaliknya, jika salah menjejakkan kaki, maka blusss… kaki akan terperosok hingga selutut, bahkan bisa lebih. Ketika kaki ditarik – dengan susah payah — biasanya si sandal memilih tinggal di dasar sana. Begitulah kejadian berulang, dan berulang lagi.
Anda tentu berpikir, bagaimana dengan ojek-ojek yang kami kendarai? Ah, tukang ojek itu bekerja lebih keras. Menarik motor yang terperosok di lumpur, bukan pekerjaan enteng. Kami pun bahu-membahu membantu tukang ojek melepaskan diri dari kubang jalan berlumpur tadi. Percayalah, aroma wangi saat berangkat, sudah berubah menjadi aroma keringat bercampur lumpur beberapa jam kemudian.
Begitulah… setiap dihadang jalan berlumpur, penumpang berjalan kaki puluhan meter. Di jalan setapak yang keras, barulah kami membonceng lagi. Rasanya belum pas pantat menempel di jok motor… rem kembali berderit, motor pun berhenti. Itu artinya kami harus turun lagi, karena di depan tampak jalan berlumpur. Menyesal saya tidak menghitung berapa kali naik dan turun jok motor. Menyebut ratusan, rasanya berlebihan…. Puluhan? Bisa jadi.
Tiba-tiba, seorang teman di depan sana nyeletuk, “Ini baru yang namanya blusukaaan….” Derai tawa kami pun menghambur, di tengah napas ngos-ngosan dan peluh bercucuran. Anda tahu? Si empunya celetukan itu, pada ruas jalan yang menukik tajam di depan, terjerembab ke parit…. Rupanya, rem ojek yang dinaikinya tidak begitu pakem.
Sungguh, semua keletihan sirna manakala memasuki desa Rogdog di Madobag, Siberut Selatan. Bunyi aliran air di sungai berundak dan berbatu, jika diperhatikan dengan seksama, memang seperti menggemakan efek suara rog-dog-rog-dog…. Kukira, itulah asal-usul penamaan Desa Rogdog.
Sebelum memasuki wilayah dan rumah adat (uma besar) di pedalaman hutan, kami harus menunggu di sebuah rumah singgah di tepi jalan. Selesai “protokoler” adat, kami baru diizinkan menuju uma di pedalaman. Dari batas rumah singgah itulah sepeda motor boleh berada. Itu artinya, menuju ke dalam, kami harus berjalan kaki sekitar tiga kilometer.
Beberapa kali menyeberang batang sungai yang sama (karena bentuknya meliuk-liuk). Si pemandu berjalan paling depan. Kami tidak bisa berjalan berdampingan. Jalan yang benar-benar pas dengan ukuran telapak kaki itu, memang harus dilalui dengan beriring-iringan. Kalau toh kami harus menyeberangi sungai, ya harus mengikuti yang di depan. Tinggi air sungai memang hanya sebatas lutut. Jika kemudian saya kisahkan ada satu teman yang terendam sedada… itu karena dia ‘kreatif’, mencoba mencari jalur jalan sungai sendiri…. Ingin tampil beda….

Di uma adat pedalaman Siberut Selatan inilah kami tinggal. Foto: Istimewa
Sekitar 45 menit kemudian, kami sampai pada rumah kayu berbentuk panggung. Ukurannya sekitar 15 x 15 meter. Kami pun berkenalan dengan Sikerei, sebutan untuk sang ketua adat. Ia bertelanjang dada, demikian pula istrinya… ehm…. Bisa kuduga, tradisi itu tidak lama lagi bakal tergerus. Mengapa? Anak-anak mereka sudah berpakaian lengkap.
Rasanya, belum lama kami berbasa-basi sambil menyantap rebusan singkong… senja pun merayap. Kami harus mandi, selagi masih bisa melihat. Bergegas mandi di dinginnya air sungai yang jernih. Ohhh… betapa desir rasa senang bergelegak, demi merasakan sensasi mandi bertelanjang bulat di tengah sungai, yang di kanan-kirinya pepohonan hutan yang lebat.
Makan malam kami, adalah makan malam nasi bungkus bekal perjalanan tadi. Itulah makanan dari peradaban luar terakhir. Sebab untuk besok pagi dan selanjutnya, kami makan dan minum, makanan dan minuman yang dihidangkan keluarga Sikerei. Nasi putih, rebusan mie instan, diaduk-aduk di atas tampah bambu…. Kami duduk –jongkok pun boleh– melingkar berhimpit-himpitan, menjumput makanan itu sesuap demi sesuap.
Ada dua tampah-bambu untuk berdelapan. Saya, tentu saja memilih makan di tampah-bambu bersama Sikerei dan istrinya yang bertelanjang dada itu. Usai menyeruput kopi dan ngobrol dengan bantuan penerjemah lokal, tidur adalah destinasi selanjutnya. Nyonya Sikerei masuk dan sejurus kemudian keluar membawa kelambu besar. Kelambu sumbangan pemerintah daerah, untuk melindungi para tamu yang datang menginap, dari serangan nyamuk hutan.
Tempat tidur tamu adalah di rumah adat bagian depan…. Terbuka. Maka, dengan kepala menengadah, dari balik kelambu, tampak langit begitu cerah. Bintang-gemintang berkerlip begitu indah. Dihanyutkan nyanyian binatang malam, serta pemandangan langit yang menakjubkan, mimpi pun menjemput. Malam itu, kami benar-benar tidur berselimut bintang-gemintang di pedalaman hutan Siberut.
Dua hari, kami harus kembali ke peradaban kota. Ada sejumput rasa enggan. Bukan karena kerasan tinggal di tengah hutan, lebih karena sandal kami tinggal sepasang. Oh Bapak Presiden, seandainya saja gegap-gempita pembangunan infrastruktur itu menjangkau pedalaman Siberut, niscaya Indonesia akan menjadi utuh, tampaknya. ***